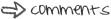Tik, tak, tik, tak. Jam tangan Shinta tak henti-hentinya berdetak. Jarum jam telah bergerak empat angka sejak ia tiba dan mulai menanti. Matahari telah bergeser lima derajat ke arah barat, membuat bayangan tubuhnya yang semampai sedikit memendek. Berdiri ia di sana, di antara pedagang asongan yang lalu lalang menjajakan rokok dan air mineral, tukang semir sepatu yang menawarkan jasa kepada pria-pria perlente yang lewat, dan supir-supir yang berusaha menjejalkan semua orang ke dalam angkot yang kelihatannya bisa meledak kapan saja. Dua puluh menit ia telah berdiri di sana, menolak tawaran semir, rokok, dan tumpangan, karena hanya satu yang akan dia terima, yaitu Rama.
*******
Setengah berlari, Rama menyusuri koridor terbuka. Asin peluh yang bercucuran di kening dan membasahi bajunya tak lagi ia perdulikan. Setelah memarkir sepeda motornya sembarangan, ia bergegas memasuki area terminal. Matanya awas, menjelajah mencari sosok gadis kecil berkuncir kuda yang ada dalam ingatannya. Bagaimana rupanya sekarang, semakin cantikkah? Fokus, ia harus menemukan Shinta, bukannya pengamen yang sibuk sendiri menghitung receh di pojok atau tukang parkir yang terus-menerus meniup peluitnya. Sial, batinnya. Mata dan kakinya terus menyusur terminal itu, sementara otaknya menyusur waktu, kembali ke sepuluh tahun yang lalu.
Rama kecil baru saja kembali dari sekolah. Cepat-cepat ia mengganti seragamnya yang sudah mulai terlalu sempit dengan kaos asal-asalan yang ditariknya dari lemari. Tubuhnya yang semakin meninggi membuatnya tak lagi nyaman mengenakan seragam putih biru itu. Ingin rasanya ia cepat-cepat bermetamorfosis menjadi siswa SMA, dengan seragam putih abu-abu yang gagah, tapi apa daya, ia masih harus menunggu dua tahun lagi. Ia mendesah, menyesali waktu yang berjalan begitu lambat, sampai tiba-tiba suara deru mobil membuyarkan angan-angannya akan masa SMA yang indah. Ia berjalan keluar dan menemukan sebuah Mitsubishi Colt Diesel terparkir di depan rumah tetangganya.
Beberapa orang bertampang kasar keluar dari rumah itu, menggotong barang demi barang yang dikenalinya sebagai sofa di ruang tamu, meja makan, meja rias, dan perabotan-perabotan lain milik tetangganya. Ia hanya berdiri di sana, terheran-heran.
“Rama,” suara lembut seorang anak perempuan dari balik pagar membuyarkan lamunannya.
Rama tersentak. Shinta sudah berdiri di depan rumahnya, tetap dengan pita merah jambu di kuncir ekor kudanya. Shinta, entah sejak kapan ia berubah menjadi sedemikian cantik. Kulitnya yang putih, bulu matanya yang lentik, dan tubuhnya yang semakin meninggi sejak ia menginjak usia remaja membuat Rama tergila-gila padanya. Padahal ia sangat ingat, dulu sekali, sebelum ada cinta di hatinya buat Shinta, ia sering tak memperdulikan rengekan cengeng gadis itu. Cewek begitu menyebalkan, pikirnya. Namun sekarang, ketika bunga cinta itu telah mekar sempurna, Shinta tak lagi ada pada kebiasaannya merengek, dan sepi berdesir di hati Rama. Ia rindu isak tangis Shinta.
“Rama,” panggil Shinta lagi. Kali ini ia sudah berdiri persis di depan Rama, membuka pagar bagi dirinya sendiri, kebiasaan lama, “Kenapa nggak jawab, sih? Dari tadi Shinta panggil-panggil.”
Rama gelagapan, “Maaf, maaf,” ujarnya, “Itu kenapa, ya? Kok barang-barang di rumah Shinta dikeluarin semua?”
“Iya, Shinta mau pindah,” jawabnya pelan. Raut wajah manisnya seketika berubah sendu. Ingin rasanya Rama menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya dan membelai helaian rambut indahnya. Hanya saja, tak cukup keberanian yang ia punya.
“Papa dipindahin ke Bandung,” lanjutnya mencoba menjelaskan, “Shinta sedih. Shinta nggak mau pindah. Shinta nggak mau jauh dari temen-temen. Shinta nggak mau jauh-jauh dari Rama.”
Oh, hati Rama seketika serasa ingin meledak. Ia bahagia dalam kesedihan. Ternyata di dalam hati gadis itu, kehadiran Rama sangat berarti. Ia bahagia, tapi kebahagiaan itu tak ada artinya karena sesaat lagi jarak ratusan kilometer akan memisahkan mereka. Sungguh miris, mengapa ia harus sadar bahwa cintanya tak bertepuk sebelah tangan saat Shinta justru akan menjauh dari kehidupannya?
“Shinta,” Rama mencoba berkata-kata, “Rama pasti kangen sama Shinta.”
Gadis itu tersenyum lembut. “Shinta juga.”
Dan sore itu, diiringi deru Mitsubishi Colt Diesel dan celoteh para pekerja yang mengangkut-angkut barang, mentari senja jadi saksi romantisme dua remaja yang menemukan esensi dari sebuah perasaan tulus yang bernama cinta.
*******
Shinta lelah. Perjalanan Bandung-Jakarta ternyata cukup melelahkan, ditambah lagi ia harus menanti dan menanti tanpa henti. Satu jam telah ia lewati dengan ditemani pedagang asongan yang tak henti-hentinya menawarkan air mineral, permen, dan tissue basah kepadanya dan hanya dijawabnya dengan gelengan kepala. Kini, keyakinannya akan kehadiran Rama semakin menipis. Saat ia menulis suratnya kepada Rama beberapa bulan yang lalu, mengabarkan kedatangannya ke Jakarta, ia yakin Rama masih mengingatnya walau selama sepuluh tahun pegunungan memisahkan mereka. Mereka punya cinta. Namun kini, tak lagi ia berani berharap. Sepuluh tahun tanpa komunikasi, bukan mustahil jika saat ini Rama telah miliki kekasih hati yang lain. Toh dulu Shinta pergi begitu saja. Dan sekarang ia sadar, cinta saja tak akan mampu bertahan tanpa komunikasi, tapi nampaknya, kesadaran itu datang sedikit terlambat.
Miris. Ia tertawa sendiri. Sepuluh tahun yang lalu ia pergi begitu saja dari kehidupan Rama tanpa membawa apa-apa selain cinta. Bahkan deretan angka-angka untuk membunyikan telepon di rumah lelaki itu pun ia tak punya. Dan kini ia belajar, tidak menyimpan nomor telepon tetangga adalah sebuah kebodohan mutlak.
*******
Hari-hari sesudah kepindahan Shinta menyisakan lubang di hati Rama kecil. Ia menghabiskan masa-masa remajanya dengan merindukan pita merah jambu di kuncir ekor kuda itu. Bukannya tak ada gadis-gadis yang mencoba mendekatinya, tapi tak satu pun digubrisnya, seolah hatinya telah terkunci dan kuncinya ia buang jauh ke Laut Jawa. Detik demi detik ia lalui dengan mengkhayalkan Shinta jauh di atas sana. Ia tahu Shinta juga punya perasaan yang sama padanya, tapi kenapa tak sekali pun dering telepon di ruang keluarga itu berasal darinya? Kenapa tak sekali pun amplop-amplop coklat di meja ruang tamu itu berisi tulisan tangannya? Kenapa?
Hingga suatu hari di bulan November tiga bulan yang lalu, sebuah amplop merah jambu menarik perhatiannya. Amplop itu terkubur bersama amplop-amplop coklat tak berguna lainnya, tapi seolah ada magnet yang menariknya, Rama seketika langsung mengetahui ada yang berbeda di tumpukan surat yang sejak lima tahun yang lalu tak pernah lagi ia gubris keberadaannya. Dan betapa bahagianya ia, ketika melihat barisan huruf-huruf yang ditulis dengan penuh cinta itu.
Namun, kebahagiaan Rama telah menguap sempurna sekarang. Sendiri, ia terduduk lemas di salah satu bangku yang tersedia di terminal itu. Peluh membanjiri tubuhnya. Sudah tiga kali ia berkeliling tanpa hasil. Tanda tanya pun sudah terlontar ke mana-nama, tapi apa daya, tak ada informasi yang dapat membantunya melacak keberadaan Shinta. Dalam satu jam ada tiga bus tiba dari Bandung, dan tak ada yang tahu di bus yang manakah Shinta menghabiskan tiga jam perjalanannya.
Sial, gerutunya, kenapa ia harus terlambat? Kenapa teman-temannya harus datang ke rumahnya subuh-subuh hanya untuk membawa sepotong kue ulang tahun dengan 22 lilin dan menyebabkan ia terlambat bangun untuk sebuah janji yang sangat penting dalam hidupnya?
Dan ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan amplop merah jambu yang telah kusut karena dibawa ke segala tempat olehnya, walaupun hanya berani dibacanya satu kali. Dibukanya pelan-pelan lipatan kertas lusuh itu dan dibacanya dengan mata nanar. Mungkin ia tak akan lagi punya kesempatan untuk bertemu Shinta, hanya karena sedikit kebodohan.
Rama,
Tak ada yang berubah di hati ini walaupun sepuluh tahun telah berlalu sejak sore itu. Tak ada surat bukan berarti tak ada cinta. Cinta ini tetap tumbuh dan berkembang walau terhalang oleh gunung dan lembah. Anggaplah sepuluh tahun ini ujian bagi engkau dan aku untuk meyakinkan diri bahwa cinta kita tidak salah memilih.
Tiga bulan lagi, di hari ulang tahunmu, aku akan menemuimu untuk meyakinkan cinta ini. Aku akan melanjutkan hidupku di Jakarta, kembali ke pelukanmu. Jika memang kau masih menyimpan asa padaku, dan aku yakin itu, jemputlah aku di Stasiun Gambir. Jam 10.30.
Dan cinta kita akan bermekaran selamanya.
Cintaku padamu,
Shinta
Jemputlah aku di Stasiun Gambir.
Jemputlah aku di Stasiun Gambir.
Jemputlah aku di Stasiun Gambir.
Rama mendengar gaung suara itu berulang-ulang dalam kepalanya. Terlonjak ia dari kursi reyot yang sedang didudukinya, di mana ia sekarang? Sialan, gerutunya dalam hati. Ia datang ke tempat yang salah. Sekuat tenaga ia berlari keluar, menghidupkan sepeda motornya, dan melaju kencang ke Gambir. Shinta, jangan pergi, kumohon!
*******
Handphone Shinta mulai bersenandung. Cepat-cepat ia mengambil benda mungil itu, menekan salah satu tombol, dan menempelkannya di telinga kirinya.
“Ya? Ada apa, Ma?” jawab Shinta.
“Kamu di mana, toh, Nak? Kenapa nggak sampe-sampe ke rumah tante? Kamu nggak kesasar, kan?” tanya ibunya di seberang sana tanpa jeda napas.
Shinta tersenyum, “Teman Shinta telat jemputnya. Mungkin dia nggak bisa datang. Shinta naik taksi, deh. Dah, Mama.”
Ia tersenyum miris. The time is up, she should have given this up from the start. Ia beranjak, menarik koper yang sejak tadi membisu di sisinya. Perlahan, ia berjalan selangkah demi selangkah, meninggalkan Gambir yang tak ubahnya lautan manusia. Meninggalkan asa akan Rama yang layu seketika walau telah dipupuk sekian lama.
*******
Berlari lagi, Rama berlari lagi. Kereta yang entah dari mana baru saja tiba, dan Gambir seperti penuh sesak oleh ribuan supporter bola dalam final Piala Dunia. Hanya saja, tak ada gawang dan lapangan hijau di stasiun ini. Lalu untuk apa manusia sebanyak ini berkumpul di satu titik di kota yang luas ini? Sebagian dari mereka baru menjejakkan kaki di tanah Jakarta, sebagian menjemput saudara mereka yang baru tiba, dan sebagian lagi memang mencari sesuap nasi di sana. Ia tidak termasuk ketiganya. Rama di sana, untuk memperpanjang napas harapannya akan cinta. Dengan mata yang terus menjelajah ke segala sudut, ia menerobos masuk ke dalam stasiun, berharap Shinta masih di sana, menunggunya dengan sekotak besar cinta yang tak akan pernah bisa habis.
Dan ia tak pernah sadar, seorang gadis berkuncir kuda dengan pita merah jambu sedang berjalan selangkah demi selangkah meninggalkan Gambir, meninggalkan dirinya yang terguyur peluh.